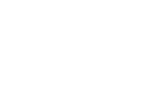Pulau Padaidori, pulau paling timur dan terluar di Kabupaten Biak Numfor, Papua, hanya dapat dijangkau melalui laut dengan perahu motor dari Kota Biak. Perjalanan memakan waktu sekitar tiga jam jika laut sedang tenang. Pulau ini langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik dan dikelilingi pulau-pulau kosong yang membentuk lanskap pesisir nan sunyi. Terumbu karang mengelilingi seluruh pulau, menjadi rumah bagi beragam ikan dan biota laut. Di beberapa tempat tumbuh mangrove dan padang lamun yang melindungi garis pantai dan menopang kehidupan masyarakat.
Empat kampung berdiri di pulau ini: Sasari sebagai kampung tertua, dan tiga lainnya—Yeri, Mnupisen (Padaido), dan Anobo—hasil pemekaran. Meskipun secara administratif terpisah, mereka tetap terhubung dalam satu kesatuan adat yang dikenal sebagai Adat Pulau Padaidori. Gereja dan pemerintah kampung pun mengikuti pembagian ini, namun dalam praktiknya, ketiganya—adat, gereja, dan pemerintah—berjalan bersama dalam menjaga keteraturan sosial dan harmoni warga. Tiga kekuatan ini tidak hanya hidup berdampingan, tetapi saling mengikat, saling menguji, dan membentuk tatanan sosial yang rumit namun bertahan.

Adat: Sistem Sosial yang Hidup
Adat di Padaidori bukan sekadar tradisi. Ia adalah sistem hukum tidak tertulis yang mengatur siapa boleh mengambil apa, di mana, dan kapan. Dari urusan pernikahan, kematian, hingga siapa yang boleh masuk hutan atau memancing di wilayah tertentu, semua tunduk pada aturan adat. Legenda-legenda seperti Manggana, Inserennanggi, dan Ikako Mampairamo bukan sekadar cerita pengantar tidur; mereka adalah kode etik yang ditanam sejak kecil.
Tokoh-tokoh adat—mananwir keret, mananwir mnu, dan tua-tua adat—menjadi penentu keadilan lokal. Ketika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya tidak dilakukan lewat dokumen, tapi lewat musyawarah, ritual, dan restitusi sosial. Belum ada kasus, dimana pelanggaran diselesaikan oleh negara melalui pengadilan negeri, karena kepercayaan masyarakat pada mekanisme penyelesaian secara adat masih utuh.
“Kami ini hidup bukan hanya dari laut, tapi juga dari aturan dan nilai-nilai adat yang menjaga laut itu.” ujar Felix Weyai, Mananwir Mnu Sasari-An Nobo.
Namun, sistem ini tidak kebal terhadap guncangan. Migrasi, tekanan ekonomi, dan hilangnya pengetahuan generasi muda telah mengikis beberapa nilai. Tanpa dokumentasi dan regenerasi, kekuatan ini bisa pudar dalam satu generasi.
Pemerintah Kampung: Jembatan antara Negara dan Adat
Pemerintah kampung di Sasari, Anobo, Yeri, dan Mnupisen tidak bisa bekerja seperti birokrasi biasa. Kepala kampung harus lihai membaca suasana sebelum melaksanakan pembangunan, seperti saat membangun jalan atau prasarana umum lainnya. Dalam banyak kasus di tempat lain, proyek infrastruktur sering kali gagal karena tanpa sadar melanggar wilayah sakral atau melewati sup—pembagian ruang adat—tanpa izin atau musyawarah adat.
Namun, bila dijalankan dengan penuh kepekaan, pemerintah kampung justru menjadi penghubung penting. Ketika ada program dari pemerintah provinsi atau nasional yang masuk, mereka berperan menerjemahkannya ke dalam bahasa lokal—baik secara harfiah maupun kultural. Misalnya, dalam pembangunan menara telkomsel, pemerintah kampung bekerja sama dengan mananwir mnu untuk menyepakati dan memastikan lokasinya sesuai dan sah secara adat.
“Kami bukan hanya menjalankan program dari atas, tapi juga menjaga agar program itu tidak merusak hubungan dengan adat dan gereja,” ungkap Bapak Buce Rumborias, mantan Kepala Kampung Anobo.
Selalu ada tantangan dalam kolaborasi ini karena masing-masing lembaga memiliki mandat yang berbeda. Namun, praktik ini menjadi bukti bahwa pembangunan modern tidak harus mengorbankan tatanan lokal.
 Gereja: Rohani, Sosial, dan Penengah
Gereja: Rohani, Sosial, dan Penengah
Gereja di Padaidori, seperti Jemaat GKI Yahya Sasari dan Jemaat GKI Petra Mnupisen-Yeri, tidak hanya berbicara soal keselamatan jiwa. Mereka membina moral, mendidik anak-anak, membantu warga jemaat saat sakit, bahkan menyalurkan bantuan ketika bencana alam melanda. Dalam konflik antar warga, pendeta seringkali dipanggil bukan untuk berkhotbah, tapi untuk menengahi.
“Kami percaya Tuhan, tapi kami juga mendukung adat. Gereja datang bukan untuk menghapus adat, tapi mendampingi,” jelas tokoh agama dari Jemaat GKI Yahya Sasari.
Hubungan antara gereja dan adat bukan hanya harmonis, tapi saling memperkuat. Salah satu bentuk kolaborasi paling nyata adalah dalam praktik sasisen—penutupan sementara wilayah laut secara adat untuk melestarikan sumber daya. Meski akar tradisinya berasal dari adat, kekuatan sasisen semakin diakui ketika pendeta turut memberkati dan memanjatkan doa dalam prosesi penutupannya.
Doa dari gereja memberi dimensi spiritual yang diyakini membawa berkah panen ikan yang melimpah saat masa buka tiba. Sebaliknya, pelanggaran terhadap sasisen dipandang sebagai pelanggaran ganda—baik terhadap hukum adat maupun terhadap kehendak Tuhan.
“Kalau sudah didoakan majelis di gereja, itu berarti Tuhan ikut menjaga laut,” ujar Steven Weyai, Mananwir Er. “Jadi tidak ada yang berani langgar.”
Gereja juga menjadi penyeimbang antara adat dan modernitas. Dalam banyak kasus, pendeta bekerja sama dengan tua-tua adat untuk menyelesaikan persoalan secara simultan: adat membersihkan secara sosial, gereja mengampuni secara spiritual. Dengan demikian, di Padaidori, iman dan tradisi berjalan beriringan dalam menjaga tatanan hidup masyarakat.
Sinergi Tiga Tungku: Adat, Pemerintah, dan Gereja
Tiga kekuatan ini—disebut “tiga tungku” oleh masyarakat—tidak bekerja sendiri. Mereka menopang satu sama lain, meski terkadang saling bertabrakan. Konflik bisa muncul: pemerintah ingin membuka lahan, adat melarang; adat ingin menutup laut (sasisen), pemerintah ragu; gereja menekankan pengampunan, adat menuntut ganti rugi. Tapi kekuatan mereka justru terletak pada kemauan untuk duduk bersama.
Salah satu kisah paling mengesankan terjadi ketika sekelompok masyarakat dari luar Pulau Padaidori menangkap ikan hias di kawasan terumbu karang yang telah ditetapkan sebagai sasisen permanen. Pelanggaran semacam ini bukan yang pertama, dan telah berulang kali mengusik ketertiban adat. Menyadari hal itu, Mananwir Mnu Sasari-An Nobo segera bertindak dengan menegur para pelaku. Menyusul tindakan tersebut, pemerintah kampung menginisiasi musyawarah bersama tokoh adat dan tokoh gereja untuk mencari solusi jangka panjang. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mengirim surat teguran dan pemberitahuan kepada masyarakat di pulau-pulau tetangga. Surat tersebut disampaikan melalui gereja-gereja setempat untuk dibacakan saat ibadah Minggu pagi, dengan harapan pesannya menjangkau seluruh warga. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana tiga kekuatan utama—adat, pemerintah, dan gereja—yang kerap berjalan dengan logika masing-masing, mampu bersatu menjaga satu nilai yang lebih besar: harmoni.
Apa yang Perlu Dijaga ke Depan
Harmoni ini bukan jaminan. Ia harus terus dirawat—dengan regenerasi pemimpin adat, dokumentasi nilai lokal, pelibatan gereja dalam isu sosial, dan pemerintah yang bekerja tidak sekadar dari meja kantor. Jika salah satu dari tiga kekuatan ini melemah, keseimbangan akan terguncang.
“Generasi muda harus paham tentang adat. Kalau tidak, adat/budaya asli Padaidori akan hilang oleh kemajuan.” ucap Bapak Costant Rumabar, Mananwir Sup Mnuk An Nobo. “Adat itu bukan milik orang tua saja, tapi warisan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh anak cucu kita.”
Padaidori telah membuktikan bahwa komunitas kecil pun bisa punya sistem sosial yang kompleks dan fungsional. Di tengah dunia yang sering membenturkan tradisi dengan kemajuan, Padaidori justru merajut keduanya.
Kini, tanggung jawab menjaga keseimbangan ini perlahan berpindah ke generasi muda. Tidak cukup hanya mengetahui cerita, mereka perlu hadir dalam musyawarah kampung, terlibat dalam pemetaan wilayah adat, dan belajar langsung dari tetua. Dengan memahami peran masing-masing kekuatan sosial, mereka bisa menjadi jembatan antar-zaman—menghormati warisan lama sambil menyesuaikannya dengan tantangan baru.
“Saatnya generasi muda berdiri, belajar dari para mananwir, dan melanjutkan peran sebagai penjaga laut, hutan, dan nilai-nilai sosial. Karena tanpa mereka, kisah Padaidori bisa berakhir bukan karena bencana, tapi karena dilupakan”, Constant Rumabar, Mananwir Sup Mnuk An Nobo.
(ST/RK)
Copyright 2025 Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut (ILMMA). Hak cipta dilindungi undang-undang. Setiap kutipan harus menyebutkan ILMMA sebagai sumber.